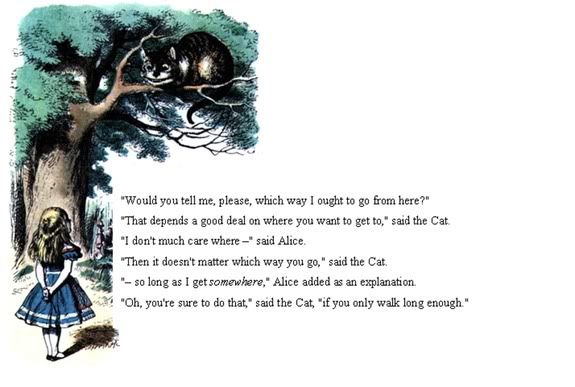 | |
| sumber: http://i228.photobucket.com/albums/ee59/Spiritof76man/cheshire_cat_2BEST.jpg |
Bismillah…
Alhamdulillah masih diberi
kesempatan untuk mendongeng lagi, di tengah-tengah hujan baris-baris excel
untuk calculation sheet hehe. Oke, jadi apa yang mau saya dongengkan hari ini?
Kemarin malam, sepulang ngajar
seperti biasa (harus) melahap jalanan kota Bandung. Dan seperti biasa pula,
mata melihat banyak hal yang menarik di jalanan. Karena kemarin otak saya
sedang enak buat berpikir (atau ngelamun?), jadilah pikiran saya kembali ke
saat saya kuliah pada siang harinya.
“Jadi cita-cita
itu dua (setidaknya), jangka panjang dan jangka pendek. Oke lah, kalau jangka
panjang susah, yang jangka pendek aja deh. Kira-kira 5 tahun ke depan kamu mau
jadi apa? Kalau kamu tidak punya cita-cita, ya susah. Kamu akan
terombang-ambing dalam hidup. Ini lebih penting dari sekedar kuliah PSK
(Pengantar Sistem Kontrol) lho!” Kami tertawa setuju saja. Karena hampir
seluruh waktu kuliah habis tidak untuk membahas fenomena kontrol suatu sistem.
“El*o, kalau kamu punya cita-cita apa?” tanya
kaprodi saya kepada salah seorang kawan.
“Ehm, kuliah ke
Jepang Pak!” jawabnya dengan mantap.
“Nah, bagus. Berarti
kamu harus mempersiapkan segalanya kan? Bahasa Jepangnya, ya segalanya lah…”
dan beliau membahas dengan panjang lebar tentang persiapan untuk melanjutkan
studi ke luar negeri.
“Nah, kalau kamu
Mas. Kamu mau jadi apa?” tanya beliau ke saya. Waduh, otak saya mulai memilih
beberapa cita-cita yang sudah saya patok di dalam kepala dan hati—memilih yang
paling pas dikatakan di sini.
“Punya
perusahaan, eh pabrik pembuatan senjata Pak!”
“Jangka panjang
atau jangka pendek?”
“Jangka panjang
Pak,” jawab saya.
“Ehm, lalu kamu
berasal dari keluarga yang oang tuanya mampu untuk memodali kamu mas?”
“Tidak Pak,” jawab saya tegas.
“Lalu, kamu perlu
mengumpulkan modal kan?”
“Yo, eh iya Pak.”
“Jadi, kamu
lebih memilih bekerja di Pindad karena itu sesuai bidang minat kamu atau
bekerja di perusahaan lain yang menjanjikan gaji lebih besar? Pilih mana?
“Gaji besar Pak.”
“Kenapa?”
“Agar bisa
melangkah lebih dekat kepada cita-cita jangka panjang saya Pak.”
“Hmm, bagus!
Kalau gitu cita-cita jangka pendekmu?”
“Bekerja di
perusahaan yang berhubungan dengan alat berat Pak, atau mungkin manufakturnya.”
Dari
sini saya cukupkan percakapan saya dengan beliau. Diskusi semakin menarik
dengan cerita-cerita dan pertanyaan-pertanyaan beliau kepada teman yang lain. Kami
diajak untuk mulai menyusun masa depan—atau karir setidaknya. Bahkan menyinggung
tantangan yang akan dialami wanita dalam merencanakan masa depannya. Pekerjaan ini
memiliki keuntungan ini, yang itu memiliki keuntungan itu. Tidak hanya gaji—meski
ini juga menjadi salah satu titik
berat diskusi—melainkan juga tentang pengalaman, training, dan pembelajaran
sosialnya. Jujur, di kepala saya mulai
lebih jelas lagi strategi mengenai apa yang kurang dan lebih dari saya untuk
mengejar suatu karir di bidang tertentu.
Namun
di jalanan saya melihat yang lain…
Jika di kelas kami membicarakan profesi ini
denga benefit ini, maka saya diingatkan kembali bahwa ada orang-orang yang
tidak seberuntung kita—kami. Jangankan memilih jalan dan cara-cara untuk
mengejar karir tersebut, tahu bahwa karir itu pun eksis belum tentu.
Satu
hal yang paling membuat saya galau (cie galau juga akhirnya pak penulis),
adalah anak-anak kecil yang harus turun ke jalan untuk menjadi—yah, pastinya
tahu lah Anda semua. Mau memberi takut
menjadikan mereka kebiasaan, atau parahnya hanya jadi setoran pada orang dewasa
yang mengeksploitasi mereka. Namun, mau tidak memberi kok ya berasa kejam. Jam segitu
masih di jalanan apakah besok tidak ngantuk saat sekolah? Atau malah tidak
sekolah? Padahal katanya sekolah sekarang gratis kan?
Akhirnya
karena terlalu lama galau lampu lalu lintas keburu jadi hijau. Sungguh suatu
ironi yang menusuk perasaan saya. Di saat siang harinya kami berdiskusi seru
tentang suatu profesi yang wah-wah, tidak jauh di luar tembok tempat sekolah
saya bertebaran permasalahan tentang mereka yang tak sempat memikirkan ingin
jadi apa mereka. Mungkin mereka memiliki cita-cita yang tinggi, namun setinggi
apa? Karena menurut saya cita-cita itu berdialektika dengan pengetahuan—dan
pengalaman. Oleh karenanya akan ada yang namanya revisi bukan?
Pikiran saya melayang kembali lebih jauh ke
belakang. Ke masa kecil saya. Mengenai cita-cita yang dari kecil menghantui
setiap mimpi saya—Insinyur. Salahkan lagu Joshua yang liriknya ada pengen bikin
pesawat itu lho. Yaah, meski di sana katanya professor, tapi semakin besar
semakin tahu bahwa mereka berprofesi sebagai engineer—dan tidak harus sampai jadi professor. Lalu, lebih galau
lagi lagu-lagu sekarang yang isinya cuma cewek ngejar cowok atau cowok ngemis
ke cewek, mau jadi apa mereka? Pengemis (nafsu)? Cih, chicken!
Ah,
entahlah. Kembali lagi, sungguh ini sebuah ironi. Ironi yang saya rasakan. Maafkanlah
jika ada yang tersinggung atau yang lain. Anggap saja sekedar dongengan dari
seorang pelajar yang mendapat gelar (yang katanya berarti besar) sebagai
mahasiswa. Mahasiswa yang sedang resah melihat negerinya mengalami ketimpangan
yang besar ini. Seorang mahasiswa yang sebenarnya tidak berasal dari kelurga
atas, bahkan sekedar membiayai kuliah pun saya harus dibayari rakyat negeri
ini. Dan sekarang sedang bekerja sambilan sebagai tukang dongeng fisika dan
matematika keliling…

0 komentar:
Posting Komentar