Hari ini saya mengingat lagi
sesuatu yang luar biasa, yang dulu sempat ingin saya tulis namun tidak
terlaksana karena rasa malas menjadi musuh yang utama. Sebuah pelajaran yang
universal, yang saya dapat dari salah satu pelatih saya: Kang Sunan Respati Dananjaya.
Untuk pecandu—perhatikan tidak saya gunakan kata pecinta karena saking cintanya
hehe, maaf Kang :P—beladiri daerah Bandung tentunya nama beliau sudah tidak
asing lagi.
Oke, jadi apa pelajarannya?
Tentu buat mereka yang belum
lupa-lupa amat dengan matematika dasar akan masih ingat grafik berikut:
Yah gitulah ya haha. Anggap itu
suatu fungsi kuadratik dengan kubah membuka ke bawah. Dan untuk sumbu x
merepresentasikan teknik beladirinya—dalam hal ini sebut saja teknik Perisai
Diri-nya, dan sumbu y merujuk kepada kebuasan, kebrutalan, atau mungkin lebih
tepat adalah potensinya untuk melukai. Sok, mangga Aa’ dan Teteh lihat lagi
grafiknya dan temukan artinya. Sudah?
Pada masa-masa awal berlatih,
seorang pesilat memiliki kebuasan atau kemampuan untuk melukai lawan yang
rendah. Lalu, seiring berjalannya waktu kemampuannya tentu meningkat. Dan potensinya
untuk melukai orang lain semakin besar. Kesombongan dan gaya berjalan yang
semakin sulit dikontrol. Rasanya tiap menemukan orang yang kira-kira bikin
sepet di mata mau dihajar saja. Rasa takut untuk memiliki masalah dengan pria
lain semakin surut. Sehingga, sebenarnya pada saat yang sama dia sedang
meningkatkan potensi dirinya terluka pula hahaha.
Hingga suatu saat dia mencapai
puncak potensi kebrutalan dan kebuasan, yaitu ketika menyentuh sumbu y. Menurut
Kang Sunan, ini akan dialami pada mereka yang sedang mendalami Teknik Harimau
dan Naga. Pada saat-saat inilah, rasa ingin cari ribut menjadi paling besar—teorinya.
Tapi saya memang mengalami sih hehe. (Pahami tentang Teknik Asli Perisai Diri
di sini)
Hingga pada titik setelah ini,
justru menurun kebrutalannya. Oleh karenanya sumbu y ini segaris dengan titik
x=0. Artinya, terdapat suatu titik balik pada kondisi ini. Setelah Teknik Naga,
masuklah orang itu ke Teknik Satria. Dia mulai resmi menjadi pelatih. Oleh karenanya,
mental sebagai pelatih juga ditempa. Diajarkan tentang pengendalian diri lebih
mendalam dan kesadaran lebih lanjut tentang makna Perisai Diri. Bahwa sesuai
namanya, beladiri ini bukanlah senjata untuk melukai namun suatu alat untuk
menangkis serangan—Perisai. Hingga akhirnya perlahan kebrutalan itu menurun. Bukan
karena TIDAK MAMPU, namun karena TIDAK MAU.
Memang itulah yang diajarkan
oleh para pelatih. Saat latihan, serangan tidak boleh ditahan. Full power, full
speed. Karena memang kemampuan juga masih cethek.
Kalau bercandanya, belum saatnya untuk berbudi luhur. “Orang dengan kondisi
serangan penuh tenaga saja kadang-kadang lawan juga masih ketawa kalau kena,
kok sok-sok an buat menahan serangan,” begitu wejangan beliau-beliau ini.
Nanti, jika memang diperlukan pelatih
yang akan membisikkan,”Jangan terlalu lepas, dia tingkatannya dibawahmu.”
Dari hasil obrolan ini saja saya
melihat kebijaksanaan yang sangat besar. Sebuah kebijaksanaan yang sebenarnya
sudah kita tahu dari dulu, tetapi lupa merupakan musuh yang utama.
TIDAK MAU, BUKAN TIDAK MAMPU
Ada beberapa hal yang cenderung aneh menurut
saya. Betapa sering diri kita menjadikan alasan ”Saya nggak mau begitu kok”, “ah,
itu gak akan terpakai”, dan kalimat-kalimat sejenis untuk malas melakukan
sesuatu yang berguna.
Contoh paling sinetronnya gini. Ada
seorang anak yang disuruh belajar nyetir sama orang tuanya tetapi dia malah
berkata,”Ah, tak perlu Ayah. Nanti toh saya akan jadi orang sukses, punya
supir. Jadi buat apa belajar.”
Atau yang agak nyerempet
kesukaan saya nih.
“Kamu belajar beladiri sana.”
“Ah, buat apa? Kan saya tidak
mau melukai orang lain.”
See? Mereka memang tidak akan melakukan hal itu. Bukan karena tidak
mau, namun karena memang tidak mampu. Pada hal yang lain pun sering kita
melakukan penolakan dengan alasan sekonyol contoh-contoh abstrak saya di atas.
“Bukan sesuatu yang luar biasa jika kau
tidak melakukan sesuatu karena tidak mampu,
bukan karena tidak mau.”
Kalau
bahasa mereka yang suka ngomongin tentang pacaran atau nikah:
“Gue jomblo karena prinsip, bukan karena
nasib!”
(Baca hal terkait ini ada tulisan saya di sini)
(Baca hal terkait ini ada tulisan saya di sini)
Sampai
di sini belum bosan kan? Nah, setelah ini saya akan sedikit mengkritisi
pemikiran beberapa orang yang benar-benar ada di sekitar kita. Dan tidak
main-main, ini tentang pilihan mereka menikah.
MENIKAH?
Menikah?
Wow, maksud kamu apa? Iya kamu, emh (Dengan gaya ngomong Dodit Mulyanto).
Jadi begini, saya pernah melihat
pada tulisan yang di-share oleh
seseorang di jejaring sosial. Kurang lebih isinya begini:
“Menikahlah saat engkau masih
belum mapan, agar anakmu merasakan nilai-nilai perjuangan pada kesulitan yang
mendera.”
Wah, romantic sekali ya? Namun
bolehkah saya melihat dari sudut pandang yang berbeda?
Memang, kesulitan dan tantangan
sangat dibutuhkan seorang anak agar menjadi dewasa. Kesulitan, pada kadar yang
sesuai akan menjadikan seseorang lebih tangguh. Sesuatu yang tidak membunuhmu hanya
akan membuatmu lebih kuat, begitu kata Tuan Krab.
Sesuatu yang tidak membunuhmu hanya akan
membuatmu lebih kuat.
Sekarang, bayangkan jika
kesulitan itu mengenai masalah hidup dan mati. Bukan hidup dan mati kita dengan pasangan kita, namun bayi kita. Pada
suatu ketika, karena kondisi ekonomi yang belum mapan—pada dosis yang parah—bisa
membuat putra kita hanya sekejap merasakan udara dunia. Itu kondisi ekstrimnya
dengan definisi belum mapan yang sangat ekstrim pula.
Selain itu, anak memang akan
belajar tentang kesulitan-kesulitan hidup, tentang bagaimana menjadi seorang
pribadi yang tangguh. Namun, sebatas itu. Dia akan kesulitan untuk mencari
contoh riil menjadi seseorang yang zuhud.
Sekarang bayangkan kondisi yang
berbeda. Kita, secara kemampuan sangat mampu untuk memanjakan dan memberikan
bermacam kemudahan kepada anak kita. Semuanya kelas satu. Namun kita tidak
melakukannya. Karena kita TIDAK MAU. Kita sedang mengajarkan bagaimana untuk
mengontrol kehidupan kita, kehidupan yang sebenarnya sangat mampu untuk
berfoya-foya namun memilih cara hidup yang sederhana. Menurut saya, itu akan
lebih terlihat keren di matanya. Orang tuanya sebenarnya SANGAT MAMPU, namun
mereka TIDAK MAU untuk menjadi budak dunia. Orang tua tersebut akan lebih mudah
untuk mengajarkan konsep zuhud, yaitu zuhud bukanlah membuang dunia dari tanganmu
tapi dia ada di hatimu, zuhud adalah
mencampakan dunia dari hatimu tapi dia ada dalam genggamanmu.
“Zuhud itu bukanlah membuang dunia dari
tanganmu tapi dia ada di hati. Zuhud adalah mencampakan dunia dari hatimu tapi
dia ada dalam genggamanmu.”
(Jika ada yang
bilang Rasul dan para shahabat itu miskin, kalian salah besar. Mereka adalah
para saudagar kaya. Mereka memang memilih hidup demikian itu karena
prinsip, bukan karena nasib. Karena kemauan, bukan mengenai kemampuan.)
So, maaf jika saya mengambil
contoh yang agak menyerempet “hal” ini. Maaf, sekali lagi maaf. Namun saya
pikir ini akan lebih mengena hehe.
Padahal, pada aplikasinya kebijaksanaan tentang “tidak melakukan bukan karena tidak mampu, namun karena tidak mampu”
tersebut sangat luas aplikasinya. Silahkan kawan-kawan cari sendiri pada bagian
kehidupan yang mana hal ini cocok diterapkan. Jika ada salah kata, saya mohon
maaf :)
Contoh lagi:
1.
Tidak mau sombong meski kehebatannya bejibun
karena dia tahu itu hal yang buruk. Bukan tidak sombong karena memang tidak ada
yang dapat disombongkan.
2.
Tidak mau mencontek karena dia tahu itu suatu
bentuk kecurangan yang hina. Bukan tidak mau mencontek karena teman sebelah
sama cupu-nya dan ada pengawas yang galaknya gokil banget.
3.
Tidak membeli mobil bersilinder besar karena
tahu itu hanya memboroskan bahan bakar dan tidak ramah lingkungan. Bukan karena
duitnya buat beli sepeda saja perlu ngutang.
4.
Ada tambahan?
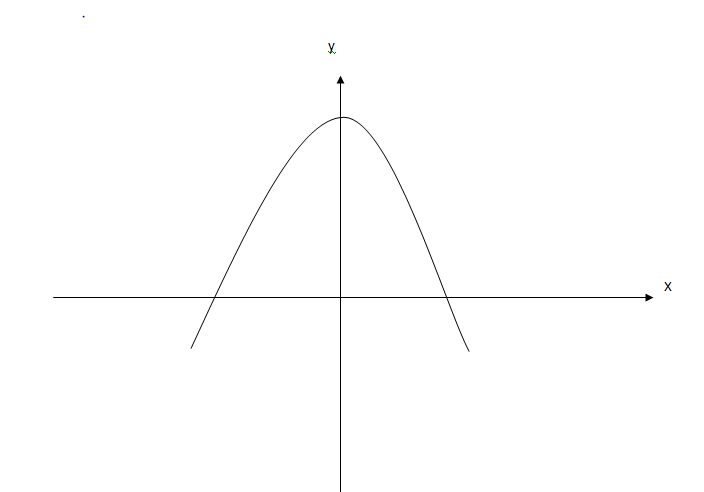

0 komentar:
Posting Komentar